Gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik dalam kondisi jenuh air dan rendah oksigen, sehingga dekomposisinya lambat. Meski hanya mencakup 3% daratan dunia, gambut menyimpan hingga 30% cadangan karbon tanah global dan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, ekosistem ini semakin terancam akibat konversi lahan, pengeringan, dan kebakaran, yang melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar dan merusak fungsi ekologisnya.
Indonesia memiliki sekitar 13,4 juta hektare lahan gambut, tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Provinsi seperti Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan serius, sebagian akibat proyek berskala besar dan kebijakan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Meskipun regulasi nasional telah diterbitkan, implementasinya masih lemah di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.
Padahal, Indonesia telah memiliki sistem data gambut yang cukup baik melalui inisiatif Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Sayangnya, data ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan berbasis ilmu.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, TROPIKA hadir sebagai pusat studi dan inovasi ekosistem gambut. Berbasis di tiga provinsi prioritas, TROPIKA mendorong kolaborasi lintas sektor dan penggunaan data ilmiah secara terintegrasi untuk mendukung pemulihan gambut secara berkelanjutan.
Visi
Menjadi pusat unggulan terdepan untuk penelitian lahan gambut tropis Indonesia, guna meningkatkan jasa ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim, serta memberikan kontribusi terhadap kebijakan pengelolaan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Misi

Direktur

Wakil Direktur

Sekretaris

Bendahara
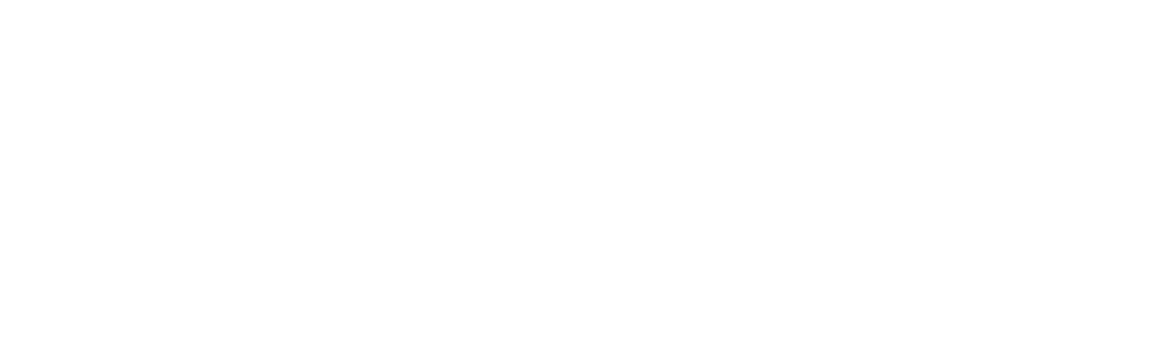
Blok C4 no.19, perum nanggela anugerah pratama, sukmajaya, kec. Tajur halang, kab. Bogor, 16320
© 2025 Pusat Kajian Gambut Tropis Indonesia. All Rights Reserved